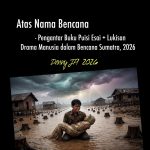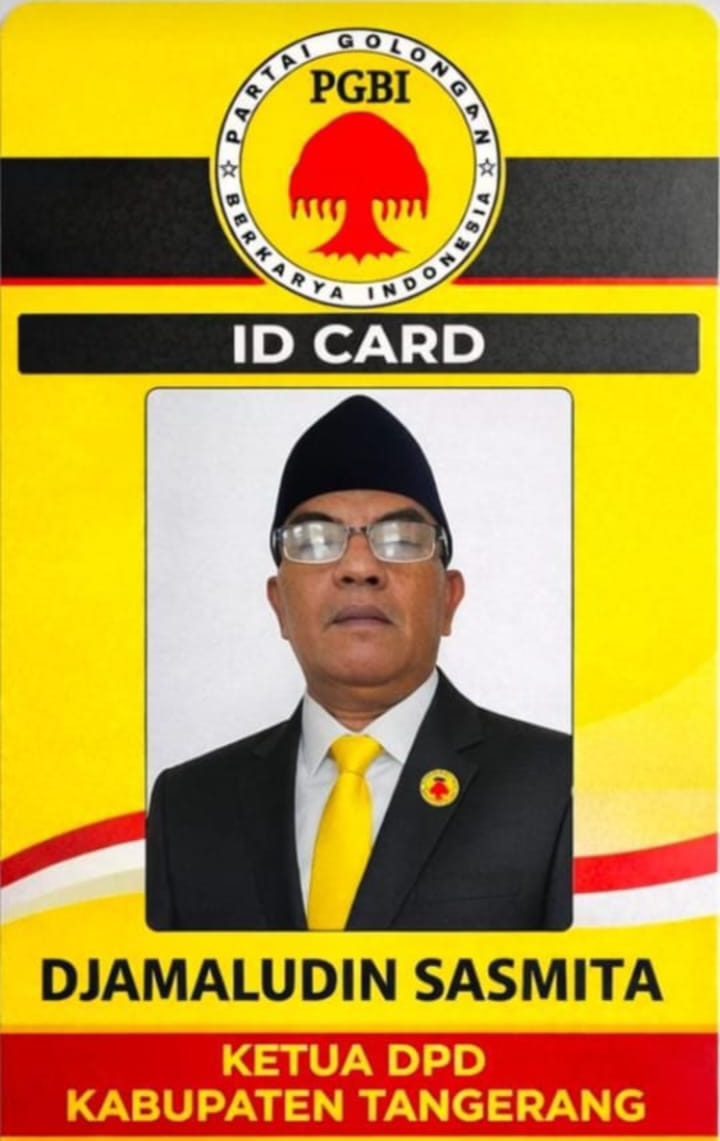TRENAKSARA.COM, Jakarta, Ahad (28/12) — Bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi dapat dipahami sebagai banjir musiman semata. Skala kerusakan dan dampak yang ditimbulkan telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan serius yang menguji kesiapan negara dalam melindungi warganya. Kerugian ekonomi akibat bencana ini ditaksir mencapai lebih dari 3,1 miliar dolar AS atau setara Rp51 triliun, sebuah angka yang mencerminkan besarnya luka sosial dan struktural yang ditinggalkan.
Guru Besar Manajemen dan Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I (UPI Y.A.I), Prof. Dr. Nandan Limakrisna, menilai bahwa bencana kali ini merupakan alarm keras atas rapuhnya ketahanan wilayah. Jalan penghubung antardaerah terputus, jembatan runtuh, sekolah serta permukiman warga rusak parah. Di banyak lokasi, listrik dan jaringan komunikasi lumpuh total, menyebabkan ribuan warga terisolasi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu.
“Jika satu peristiwa alam saja mampu melumpuhkan akses dasar seperti jalan, listrik, dan komunikasi, maka persoalannya bukan semata pada alam, tetapi pada sistem yang belum siap menghadapi risiko,” ujarnya.
Menurutnya, fakta-fakta di lapangan seharusnya cukup untuk menghentikan kebiasaan lama menyebut peristiwa semacam ini sebagai bencana tahunan. Yang terjadi, kata dia, adalah akumulasi kerentanan akibat kegagalan sistemik dalam membangun ketahanan wilayah. Alam memang menjadi pemicu, tetapi besarnya dampak menunjukkan bahwa risiko telah lama diabaikan.
Sumatera sendiri bukan wilayah asing dalam peta kebencanaan nasional. Curah hujan tinggi, kondisi geografis yang kompleks, serta perubahan tata guna lahan yang masif menjadikan risiko selalu hadir. Namun risiko, tegas Prof. Nandan, seharusnya diantisipasi melalui perencanaan matang, bukan diterima sebagai takdir yang berulang tanpa evaluasi.
Dampak paling memprihatinkan dari bencana ini adalah krisis kemanusiaan yang menyertainya. Warga yang terisolasi bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah, sementara banyak kepala keluarga kehilangan mata pencaharian dalam sekejap.
“Dalam kondisi seperti ini, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Setiap hari keterlambatan bantuan berarti meningkatnya risiko terhadap keselamatan dan martabat manusia,” katanya.
Krisis Sumatera juga membuka persoalan klasik yang kembali berulang, yakni lemahnya koordinasi. Dalam situasi bencana besar, negara diuji bukan oleh niat baik, melainkan oleh kecepatan dan ketepatan eksekusi. Ketika bantuan logistik tersendat dan distribusi tidak merata, kepercayaan publik pun ikut tergerus. Padahal, dalam kondisi darurat, kepercayaan adalah modal sosial yang paling vital.
Namun di balik hiruk-pikuk respons darurat, Prof. Nandan mengingatkan adanya pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah pascabencana kita akan kembali membangun dengan pola lama? Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa rekonstruksi sering dilakukan secara cepat, tetapi belum tentu lebih tangguh. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun ulang, dan permukiman direlokasi, namun tanpa perubahan pendekatan, bencana berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.
Sumatera, lanjutnya, membutuhkan lebih dari sekadar rehabilitasi fisik. Wilayah ini memerlukan transformasi menyeluruh dalam pendekatan pembangunan kawasan rawan bencana. Infrastruktur harus dirancang berbasis risiko, bukan hanya memenuhi standar minimum. Jalan dan jembatan harus mampu bertahan terhadap curah hujan ekstrem, sementara sistem listrik dan komunikasi wajib memiliki cadangan serta jalur alternatif agar isolasi tidak kembali terulang.
Selain infrastruktur fisik, ketahanan ekonomi masyarakat lokal juga harus menjadi agenda utama pemulihan. Banyak warga terdampak bergantung pada sektor informal dan usaha kecil. Ketika bencana datang, mereka kehilangan rumah, modal, dan sumber pendapatan sekaligus. Di sinilah peran koperasi, usaha berbasis komunitas, serta skema pembiayaan darurat berbasis bagi hasil menjadi sangat relevan.
“Pemulihan tidak boleh berhenti pada bantuan konsumtif. Yang dibutuhkan adalah pemulihan penghidupan agar masyarakat dapat kembali berdiri dengan lebih kuat,” tegasnya.
Pemerintah pusat dan daerah didorong menjadikan bencana Sumatera sebagai titik balik kebijakan nasional. Anggaran penanggulangan bencana tidak semestinya hanya terserap untuk tanggap darurat, tetapi juga diarahkan secara serius pada pencegahan dan kesiapsiagaan. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk ketahanan, menurut Prof. Nandan, akan menghemat puluhan rupiah kerugian di masa depan.
Dunia usaha pun tidak bisa memandang krisis ini dari kejauhan. Kerugian Rp51 triliun bukan hanya angka dalam laporan APBN, tetapi juga mencerminkan gangguan rantai pasok, distribusi barang, dan iklim investasi. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan ketahanan wilayah melalui kemitraan infrastruktur, logistik darurat, dan teknologi pemantauan bukan semata tanggung jawab sosial, melainkan kepentingan ekonomi jangka panjang.
“Bencana ini menguji lebih dari sekadar kesiapan teknis. Ia menguji kehadiran negara. Hadir bukan hanya lewat pernyataan dan kunjungan, tetapi melalui sistem yang bekerja cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada korban,” pungkasnya.
Sumatera kini tengah terluka. Yang dibutuhkan bukan hanya simpati, tetapi keberanian mengambil keputusan untuk mengubah cara kita membangun dan melindungi wilayah rawan. Jika krisis kemanusiaan ini hanya berakhir sebagai catatan berita dan laporan kerugian, maka bangsa ini telah menyia-nyiakan pelajaran yang sangat mahal.
Bencana memang tidak selalu bisa dicegah. Namun krisis kemanusiaan akibat bencana adalah pilihan kebijakan. Dan pilihan itu masih bisa diubah, mulai sekarang.